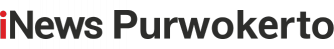Ketika Candu Dilegalkan di Masa Hindia Belanda, Opium Komoditas Paling Menguntungkan

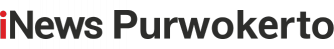

KEDIRI, iNews.id - Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadi salah satu sentra pasar opium terbesar di Nusantara pada abad ke-19. Kala itu, pemerintah Hindia Belanda mendatangkan opium dari luar negeri dan menjadi salah satu komoditas dagang paling menguntungkan kas negara.
Sejarah legalitas opium pada jaman pemerintah Hindia Belanda berawal saat Belanda mendapatkan opium dari hasil pemenangan lelang di Calcutta atau di British Singapura. Pemerintah membeli dari para pedagang swasta Belanda di Levant.
Saat itu, orang-orang Jawa dan sebagian Tionghoa sampai rela merogoh kocek hanya untuk bisa menikmati candu tersebut dan memenuhi pondok opium untuk beramai-ramai mengisap candu. Sambil duduk bersila, mereka menikmati candu hingga pandangan mereka kosong.
"Semua opium resmi yang dikonsumsi di Jawa pada abad ke-19 berasal dari Turki dan Persia atau British Bengal,” tulis James R Rush dalam buku “Candu Tempo Doeloe, Pemerintah, Pengedar dan Pecandu 1860-1910 ”.
Memang, sebelum dilempar ke pasar, opium yang masuk ke Jawa lebih dulu disimpan di gudang-gudang yang sudah disiapkan di Batavia, Semarang dan Surabaya. Bisnis opium dijalankan negara secara legal. Untuk aturan tata niaganya, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1860 membuat kebijakan Pak Opium (opiumpach), yakni kesepakatan monopoli atas penjualan opium.
Monopoli perdagangan opium diberikan negara kepada mereka yang bersedia bermufakat. Mereka yang mendapat hak istimewa itu biasa disebut pengepak, dan bekerja dalam jangka waktu tertentu dengan kewenangan berdasarkan kewilayahan, seperti kota, distrik atau provinsi.
“Di Pulau Jawa sepanjang abad ke-19, para saudagar Tionghoa membayar mahal hak istimewa ini,” kata Jamesh R Rush.“Jadi, mereka memasok pajak dalam jumlah besar kepada Pemerintah Belanda di pulau tersebut (Jawa),” katanya.
Jelang berakhirnya sistem tanam paksa, mulai tahun 1860, Pak Opium menjadi lembaga kunci yang menghubungkan sistem Pegawai Tionghoa dengan Pangreh Praja dan Pegawai Kolonial.
Sumber pendapatan yang berasal dari pajak Pak Opium merupakan yang terbesar dibanding sektor-sektor ekonomi lainnya. Betapa opium sangat diminati penduduk Jawa yang pada tahun 1883 tersebar di 22 karsidenan, di mana sejak tahun 1870 per kabupaten sebanyak 180.000 jiwa atau total se Pulau Jawa mencapai 18 juta jiwa.
Pasar opium terkaya berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pak Opium Surakarta, Karsidenan Kediri, Madiun dan Semarang hampir selalu menghasilkan pendapatan tertinggi. Selama abad ke-19, daerah-daerah tersebut menjadi tempat para pengepak opium terkuat berkuasa.
Pada saat itu hanya wilayah Priangan dan sebagian besar Banten (Jawa Barat) yang tertutup untuk operasi Pak Opium resmi. Di dua wilayah tersebut dan sekitarnya muncul kebencian lokal dari masyarakat yang menolak keberadaan opium, termasuk berani membuat larangan resmi.
Selain Surakarta, Karsidenan Kediri, Madiun dan Semarang, karsidenan di wilayah pesisir juga menjadi basis pasar peredaran opium yang besar. Rembang dan Surakarta yang saling berdekatan, bersama Kedu dan Yogyakarta di bagian selatan Jawa Tengah, juga menjadi kantong-kantong konsumen atau penghisap opium dalam jumlah besar.
Begitu juga wilayah Pasuruan, Probolinggo dan Besuki (Jawa Timur), serta Pulau Madura, konsumsi opium secara konsisten tergolong tinggi. Pada abad ke-19, menghisap opium sudah menjadi ciri umum kehidupan masyarakat Jawa di kota maupun di desa. Di setiap desa maupun kota terdapat pemakai tetap dan para penghisap yang bersifat kadang-kadang.
Sementara kelas sosial menentukan cara menikmati opium. Golongan warga biasa menghisap di pondok-pondok umum, tempat khusus untuk menikmati opium. Mereka diantaranya para pedagang keliling, pekerja upahan atau kuli, tukang, pengembara dan lain sebagainya.
Yang diisap yakni opium mentah atau candu yang disuling dan dicampur dengan penguat rasa serta bahan campuran lainnya. Alat penghisapnya buatan rumah atau batang daun pepaya sekali pakai.
“Rakyat kebanyakan mengisap campuran yang lebih rendah kualitasnya dengan menggunakan pipa sederhana dan menikmati ramuan lebih murah, seperti tike, daun awar-awar (ficus septica), dirajang halus dan dicampur dengan candu dan gula,” tulis James R Rush.
Para priyayi Jawa atau orang-orang yang lebih kaya, termasuk orang-orang Tionghoa mengisap candu yang berkualitas baik dan lebih mahal. Mereka memakai pipa-pipa penghisap yang bermutu bagus (badudan). Orang-orang Tionghoa kaya biasanya juga menikmati opium di rumah atau klub-klub opium pribadinya.
Bagi kalangan priyayi Jawa, mengisap candu sudah menjadi semacam life style. Opium menjadi sisi keramahtamahan sosial kaum bangsawan.
Pada acara pesta-pesta yang digelar para priyayi, tuan rumah hampir selalu memberi suguhan candu kepada tamu laki-laki. Di masyarakat desa dan masyarakat perkebunan, aksi bagi-bagi opium dilakukan pada saat musim panen padi dan dimulainya petik kopi.
Catatan Jaffe dan Martin dalam Oploid Analgesics and Antagonist (1976) menyebutkan orang-orang Jawa para penghisap candu meyakini opium dapat memberi mereka energi sekaligus membantu agar tetap terjaga di malam hari. Opium diyakini bisa menjadi obat sakit kepala, demam, malaria, sakit perut, diare, disentri, asma, lelah dan gelisah. Bagi kebanyakan orang, mengisap candu dapat menghilangkan perasaan tidak nyaman pada kehidupan.
Lalu bagaimana dengan orang-orang Belanda sendiri? P.A Daum dalam catatan Ups and Downs Of life in the Indies (1892), menyebut orang-orang Belanda lebih menyukai gin, yakni minuman beralkohol dari hasil fermentasi dan proses distilasi. Bagi orang- orang Belanda opium bersifat buruk. “Yang diasosiasikan dengan orang-orang blasteran yang lemah dan orang-orang jahat yang menghilang di kampung-kampung dan daeah kumuh”.
Demikian sejarah legalitas opium atau candu yang pernah berlaku di Indonesia pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.
Editor : Arbi Anugrah