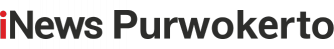Dua Hari, Satu Ironi

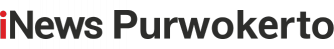

Oleh: Ahmad Sabiq
Setiap awal Mei, kita memperingati dua momentum penting secara berurutan. Tanggal 1 Mei kita memperingati Hari Buruh Internasional, sebuah momen untuk menghormati perjuangan kaum buruh, mengakui kontribusi mereka dalam kehidupan bersama, serta menegaskan hak-hak dasar para pekerja.

Sehari berselang, pada 2 Mei, kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, suatu peringatan akan pentingnya akses pendidikan yang merata dan bermartabat bagi seluruh anak bangsa, sekaligus mengenang jasa para pahlawan pendidikan.
Namun, bagaimana jika dua hari penting ini justru menghadirkan ironi bagi ratusan ribu buruh migran dan anak-anak mereka? Bagi banyak buruh migran Indonesia, terutama yang bekerja di Malaysia, kedua hari ini bukanlah perayaan, melainkan pengingat pahit hak-hak yang belum sepenuhnya terpenuhi.
Kerja keras mereka di ladang-ladang sawit, sektor konstruksi, atau sektor domestik ternyata tak serta-merta membuka jalan pendidikan bagi anak-anaknya. Alih-alih duduk di bangku sekolah, banyak di antara mereka yang belum dapat mengakses layanan pendidikan dasar, hidup tanpa status hukum yang jelas.

Merekalah yang disebut sebagai anak tanpa dokumen (undocumented children), yakni anak-anak yang tidak memiliki bentuk dokumentasi yang sah untuk tinggal di negara tempat mereka berada.
Sebagian lahir dari orang tua migran yang juga tidak berdokumen, sementara sebagian lainnya dibawa ke negara tujuan melalui jalur tidak resmi. Kondisi ini membuat mereka kehilangan akses terhadap hak-hak dasar, termasuk pendidikan, sehingga terpinggirkan secara sosial dan ekonomi.
Status undocumented yang mereka sandang sejatinya mencerminkan sistem yang ambivalen. Di satu sisi, keberadaan tenaga kerja migran sangat dibutuhkan di negara tujuan, namun di sisi lain, perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja dan keluarganya masih perlu diperkuat.

Dalam konteks ini, Linda Lumayag (2016) menunjukkan bahwa anak-anak migran sering kali tidak diposisikan sebagai subjek utama dalam kebijakan migrasi, sehingga keberadaan mereka kurang terlihat dan kebutuhan mereka kurang diperhatikan.
Sejak tahun 2002, kebijakan Pemerintah Malaysia membatasi akses sekolah negeri hanya bagi warga negara Malaysia, sehingga ribuan anak buruh migran kehilangan kesempatan untuk bersekolah. Bukan karena mereka enggan belajar, tetapi karena negara tempat mereka tinggal belum sepenuhnya hadir memberikan perlindungan.
Dalam keterbatasan itu, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan NGO, perusahaan perkebunan, hingga komunitas lokal berupaya menghadirkan pendidikan nonformal melalui pendirian Community Learning Centres (CLC) dan Sanggar Bimbingan (SB) berbasis kurikulum nasional. Namun, tantangan masih besar karena jumlah anak yang dapat dijangkau belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan.

Dalam kerangka teori kapabilitas yang dikembangkan oleh Amartya Sen (1993), pendidikan bukan hanya soal belajar, tetapi alat untuk membebaskan manusia dari keterbatasan sosial. Bagi anak-anak tak berdokumen ini, pendidikan bukan sekadar membaca dan berhitung tetapi jembatan menuju masa depan. Tanpa akses pendidikan, pilihan hidup mereka menjadi sangat terbatas.
Maka, di tengah peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional, meskipun terasa ironis, kita perlu bertanya dengan jujur: Apakah kita benar-benar menghargai buruh migran jika anak-anak mereka tetap terpinggirkan dari pendidikan? Apakah pendidikan kita benar-benar merata jika anak-anak buruh migran tidak pernah mendapat kesempatan yang sama? Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, di mana pun mereka berada.
Ahmad Sabiq
Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed
Editor : EldeJoyosemito