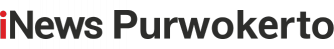Larangan Perkawinan Sokaraja-Purbalingga? Ternyata Ada Latar Belakang Sejarahnya

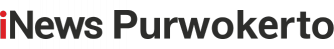

LARANGAN perkawinan atau tabu nikah, baik itu antarsuku, antaragama, antarras maupun antargolongan kiranya menjadi sebuah bagian dari fenomena sosial-budaya di dalam masyarakat.
Salah satunya yang terkenal adalah adanya larangan menikah antara suku Jawa dan Sunda.
Sebagaimana diyakini oleh masyarakat luas, adanya larangan itu merujuk pada peristiwa sejarah Perang Bubat antara Kerajaan Majapahit (Suku Jawa) dan Kerajaan Padjajaran (Suku Sunda).
Hingga saat ini, tak jarang masih banyak generasi muda yang menjadikannya sebagai momok dalam menjalin hubungan dengan pasangannya.
Terkait dengan fenomena tersebut, ternyata di tanah Banyumas sendiri juga terdapat kepercayaan serupa, yakni tabu nikah antara masyarakat di pedesaan Sokaraja-Purbalingga.
Mungkin cerita tersebut kurang populer ketimbang Babad Banyumas, maupun cerita tentang Kamandaka. Namun, ada baiknya sebagai masyarakat Banyumas, tahu dan memahami konteks dibalik adanya tabu pernikahan tersebut.
Oleh sebab itu, melalui jurnal ilmiah karya Prof. Dr. Sugeng Priyadi, M.Hum, selaku Guru Besar Pendidikan Sejarah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), berjudul “Tabu Nikah Antara Masyarakat Purbalingga dengan Sokaraja” yang terbit di jurnal ilmiah Sosiohumaniora Unpad Bandung.
Lewat tulisannya, dua hendak memperluas cakrawala kita dalam melihat fenomena itu di tengah masyarakat.
Seperti yang telah dirangkum oleh iNewsPurwokerto.id, Selasa (7/6/2022), berikut ini adalah paparan sari pati dari tabu nikah Sokaraja-Purbalingga.
Latar belakang dari konflik yang menimbulkan adanya tabu nikah tersebut terjadi pada masa peralihan Banyumas sebagai daerah mancanegara barat Kasunanan Surakarta menjadi wilayah kekuasaan Kolonial Belanda di abad 18, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1831.
Peresmian Karesidenan Banyumas oleh Belanda membuat Sokaraja yang tadinya masuk dalam wilayah Kabupaten Banyumas kemudian dimasukkan dalam wilayah Purbalingga (Brotodiredjo & Ngatidjo Darmosuwondo 1969: 75).
Dengan demikian status Sokaraja pun berubah dari sebelumnya Katumenggungan Sokaraja (wedana bupati kanoman) menjadi distrik Sokaraja.
“Kiranya, terjadi konflik antarelit Sokaraja dengan Purbalingga yang digambarkan oleh Babad Purbalingga-Sokaraja serta folklor yang berkembang di masyarakat luas.
Konflik itu diredakan dengan dikembalikannya Sokaraja ke dalam wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 1834 (Brotodiredjo & Ngatidjo Darmosuwondo 1969: 75),” tulis Priyadi dalam jurnal ilmiahnya.
Sugeng Priyadi menggunakan beberapa naskah sebagai acuan yang mewakili masing-masing kubu, yakni Cerita Raden Kaligenteng, Babad Purbalingga-Sokaraja versi Kutasari, dan Babad Sokaraja versi Hilal yang ketiganya mewakili kelompok Sokaraja, sedangkan versi yang mewakili kelompok Purbalingga adalah naskah Babad Purbalingga-Sokaraja Versi Kalimanah.
Berdasarkan isi dari naskah dari kedua versi tersebut, keduanya saling berlomba untuk berebut kebenaran atau dalam bahasa Priyadi disebut sebagai perebutan “legitimasi” dengan saling menjatuhkan satu sama lain demi kepentingan kelompoknya.
“Penuturan versi Sokaraja dan versi Purbalingga yang berbeda merupakan suatu gejala yang amat wajar dan secara pasti sering dijumpai dalam persoalan konflik di antara dua kubu. Masing-masing kubu berusaha melakukan pembenaran atas sikap dan perilakunya,” jelas Priyadi dalam jurnal ilmiahnya.
Dari keempat versi tersebut, Priyadi menemukan bahwa terdapat dua versi yang menyatakan bahwa konflik itu berakhir dengan damai dan kedua versi lainnya menyatakan bahwa konflik itu berakhir dengan konflik.
Salah satu versi yang memuat penyelesaian atas konflik antara Sokaraja-Purbalingga adalah versi Kutasari. Meskipun demikian, Priyadi menilai bahwa penyelesaian itu masih berbau konflik dengan ditemukannya tabu nikah.
“Tabu nikah adalah konflik sosial yang berlanjut hingga sekarang dan tidak dapat diketahui kapan berakhir, sementara masyarakat sekarang tidak lagi memahami konteks peristiwa yang telah terjadi. Mereka menjadi korban dari konflik orang-orang terdahulu,” imbuh Priyadi dalam jurnal imiahnya.
Menurut Priyadi, masyarakat dari kedua belah pihak meyakini bahwa pelanggaran atas tabu nikah tersebut berakibat fatal dalam kehidupan pasangan yang menikah. Ia juga menjelaskan bahwa awal mula terbentuknya keyakinan tersebut berdasarkan versi keempat adalah dari sebuah peristiwa lamaran seorang bangsawan Sokaraja terhadap putri Purbalingga.
Kala itu, pihak mempelai putri mengajukan syarat berupa tumpeng uceng. Seperti yang diketahui, uceng adalah jenis ikan yang hidup di sungai dan cukup langka populasinya.
Dengan demikian, pihak mempelai putra (Sokaraja) merasa pihak mempelai putri (Purbalingga) mengisyaratkan penolakan secara halus, sehingga muncullah tabu nikah antar Sokaraja-Purbalingga. Priyadi juga menambahkan bahwa munculnya tabu nikah tersebut bisa jadi merupakan kesalahan penafsiran.
“Sebaliknya, dari peristiwa itu muncul syarat tumpeng berisi uceng dalam tradisi lamaran pada kalangan masyarakat Sokaraja sendiri yang tidak berkaitan dengan lamaran kepada pihak Purbalingga. Tumpeng berisi uceng kemungkinan adalah tafsiran yang keliru dari orang Sokaraja terhadap tumpeng uceng yang menimbulkan tabu berbesanan antara Sokaraja dengan Purbalingga yang sampai hari ini masih berlaku,” imbuh Priyadi dalam jurnal ilmiahnya.
Selain soal lamaran itu, Priyadi juga menyebutkan bahwa adanya dugaan persaingan politik di Purbalingga antara keturunan Banyumas dan keturunan Arsantaka yang menjadi cilak-bakal munculnya tabu nikah atau larangan nikah tesebut.
Di dalam berbagai naskah dan folklor temuannya, Priyadi melihat secara samar-samar adanya hubungan antara pihak Purbalingga dan Sokaraja yang terjalin melalui perkawinan.
“Arsantaka adalah seorang demang bawahan Raden Tumenggung (RT) Yudanegara III. Anaknya yang bernama Arsayuda dijadikan menantu oleh Yudanegara III, bahkan di kemudian hari menjadi bupati Purbalingga dengan gelar Dipayuda III. Jadi, tabu nikah antara Sokaraja dengan Purbalingga merupakan larangan perkawinan incest untuk menikahi wanita yang berasal dari klen yang sama (Bertens 1991: xxxiv),” tambah Priyadi dalam jurnal ilmiahnya.
Terlepas dari peristiwa manakah yang melatarbelakangi tabu nikah tersebut? atau versi manakah dari kedua pihak, Sokaraja-Purbalingga itu yang benar? yang jelas fenomena larangan nikah atau tabu nikah itu telah mentradisi dalam benak masyarakat di kedua belah pihak.
Mirisnya, hal itu akan terus bergaung secara turun-temurun tanpa pernah diketahui apa yang melatarbelakanginya atau hanya sebatas kesadaran kolektif dalam bentuk larangan. Maka dari itu, Priyadi menegaskan bahwa selama masyarakat masih memercayai adanya tabu nikah, tabu nikah itu akan selalu ada, kecuali tabu nikah itu ditinggalkan.
Editor : EldeJoyosemito