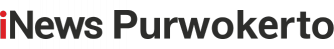Kiai Mojo Ulama Kepercayaan Pangeran Diponegoro yang Mengenyam Pendidikan di Makkah, Begini Kisahnya

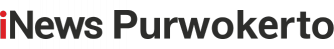

JAKARTA, iNews.id - Pada saat terjadi Perang Diponegoro antara tahun 1825-1830, ada sosok yang menjadi pendamping Pangeran Diponegoro. Dalam perang selama lima tahun yang merepotkan Belanda tersebut, tokoh ini merupakan ulama yang menjadi tangan kanan Pangeran Diponegoro.
Sosok itu sangatlah penting dalam perang Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Ia adalah Kiai Mojo yang memiliki nama asli Muslim Muhamad Halifah.

Kiai Mojo diberi kepercayaan sebagai Panglima oleh Pangeran Diponegoro dalam perang yang berlangsung lima tahun itu.
Pasukan Pangeran Diponegoro sangat tangguh dengan taktik perang gerilya yang sulit dipatahkan. Belanda mengeluarkan segala upaya dan akal bulusnya untuk mengulik apa rahasia di balik ketangguhan pasukan Pangeran Diponegoro.
Untuk mengetahui rahasia itu, pemimpin perang Belanda mengirim mata-mata ke markas pasukan Pangeran Diponegoro di Goa Selarong. Intel yang menyusup masuk merupakan orang pribumi.

Hasil amatan mata-mata diungkapkan sosok paling berperan penting dalam perang tersebut bernama Kiai Mojo. Dia lah sosok hebat, orang kepercayaan Pangeran Diponegoro yang menjadi otak pengatur strategi.
Kiai Mojo lahir dari keturunan bangsawan tahun 1782 dengan ibu bernama RA Mursilah yang merupakan adik Sultan Hamengkubuwono III. Ayah Kiai Mojo bernama Iman Abdul Ngarip, seorang ulama besar dari Keraton Surakarta dengan sebutan Kyai Baderan.
Hal itu membuat Kiai Mojo tumbuh dalam tradisi keagamaan yang kuat. Ilmu agamanya semakin sempurna ketika mendapat kesempatan belajar di Makkah.

Selain memahami Al-Quran dengan sangat sempurna, Kiai Mojo juga menguasai sejarah dan manuskrip-manuskrip Arab. Tidak hanya menguasai ilmu agama dan sejarah, Kiai Mojo juga memiliki kemampuan berorganisasi.
Berkat kepribadiannya yang rendah hati meski berilmu tinggi, dia bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Dia membangun jaringan dan hubungan yang karib dengan banyak pesantren baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan hingga Bali.
Kiai Mojo pernah menjadi penghubung antara Kraton Surakarta dan Kerajaan Buleleng di Bali. Kemampuan itu pula yang memudahkan dia memobilisasi kekuatan ulama dan santri saat dibutuhkan. Itu terbukti ketika Kiai Mojo mendukung penuh Pengeran Diponegoro.

Para santri dan tokoh agama bersatu mendukung Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda. Kedua kelompok tersebut pun turut berkumpul di Selarong yang dijadikan markas perjuangan Pangeran Diponegoro.
Dalam buku 'Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785–1825', disebutkan ada sekitar 200 laki-laki dan perempuan kaum santri yang bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Beberapa di antara mereka bahkan terdapat orang Arab dan peranakan Tionghoa.
Ada juga golongan santri istana yang merupakan anggota hierarki pejabat resmi Islam dan resimen pasukan yang direkrut dari para santri keraton. Mereka semua dimobilisasi Kiai Mojo untuk ikut berperang bersama Diponegoro.

Kiai juga memobilisasi keluarga besar dan para santrinya yang datang dari tiga pesantren di Mojo dan Baderan, dekat Delanggu, dan Pulo Kadang, dekat Imogiri. Semua kiprah dan kehebatan Kiai Mojo menjadi informasi penting yang disampaikan mata-mata kepada kompeni.
Sang mata-mata tentu tidak hanya melapor kehebatan Panglima Kiai Mojo, tapi juga kelemahannya. Dari informasi-informasi penting itu, pimpinan perang Belanda menyusun strategi untuk menaklukan kekuatan Pangeran Diponegoro.
Pada 1828, tibalah saatnya bagi Belanda untuk menangkap Kiai Mojo. Saat itu, ada selisih paham antara Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro. Kiai diperintahkan untuk kembali ke tempat kelahirannya di Pajang.
Dalam perjalanannya ke Pajang, Kiai Mojo kemudian dibujuk muridnya, Kiai Dadapan agar mau bertemu perwakilan Belanda, Letnan Kolonel Wironegoro. Kiai Mojo kemudian bertemu dengan Letnan Kolonel Wironegoro pada Oktober 1828 dengan mengajukan beberapa permintaan.
Letnan Kolonel Wironegoro menyetujuinya dengan syarat Kiai Mojo bersedia menghentikan perang. Kiai Mojo melaporkan pertemuan itu kepada Pangeran Diponegoro melalui surat.
Setelah membaca surat dari Kiai Mojo, Pangeran Diponegoro marah. Lalu Pangeran Diponegoro memanggil Kiai Mojo kembali ke markas di daerah Pengasih. Pada tahun 12 November 1828 Kiai Mojo ditangkap di Desa Kembang Arum, utara Yogyakarta.
Ini menandai titik balik perjuangan Diponegoro, sampai akhirnya redup pada 1830. Pasukan Kiai Mojo lalu digiring ke Klaten, lalu dibawa ke Batavia, ditahan hingga setahun lamanya. Di awal 1830, Kiai Mojo bersama lebih dari 60 orang pengikutnya dibuang ke Minahasa.
Istrinya menyusul setahun kemudian. Kebanyakan pendampingnya itu punya posisi strategis dalam bidang kemiliteran dan keagamaan dalam pasukan Diponegoro. Mereka tiba di Tondano dan mendirikan Kampung Jawa di sana.
Kiai Mojo wafat di tempat pengasingan pada 20 Desember 1849 dalam usia 57 tahun. Roh perjuangan Kiai Mojo tertuang dalam manuskrip berbahasa Jawa huruf pegon yang ditulisnya di Tondano, Minahasa, sekitar awal tahun 1833.
Tertulis dalam manuskrip itu kalimat "berjuang untuk kepentingan kemaslahatan para hamba Allah semua, untuk kesejahteraan negeri, serta untuk kepentingan kelestarian agama Islam".
Editor : EldeJoyosemito