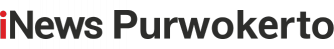Muhammadiyah Jumlah Kiainya Menurun, 3 Faktor Ini Jadi Penyebab

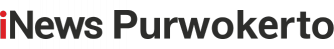

”Dengan demikian, modernitas yang selama ini menjadi ciri pemikiran dan sikap sosial Muhammadiyah telah membuat ladang yang gersang bagi tumbuhnya kiai,” tutur Syafiq.
Berbeda dengan organisasi lain, Syafiq menerangkan bahwa anak cucu seorang kiai Muhammadiyah tidak serta-merta diistimewakan. Tidak banyak orang berdatangan untuk minta berkah kepada kiai Muhammadiyah. Egalitarianisme menyebabkan kedudukan kiai dalam Muhammadiyah tidak lagi istimewa.
Dengan demikian, lanjut Syafiq, dapat disimpulkan bahwa memang terjadi penurunan kuantitas kiai dalam Muhammadiyah, dan itu berimplikasi hilangnya dominasi kiai dalam kepemimpinan. Kiai menjadi barang langka dalam Muhammadiyah.
”Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa kuantitas ulama juga menurun,” kata dia.
Syafiq pun menjelaskan perbedaan konsep antara kiai dengan ulama. Menurut dia, kiai adalah konsep antropologis. Seseorang menjadi kiai karena komunitasnya menyebutnya demikian. Jika seseorang itu berada di luar komunitasnya sangat mungkin tak seorang pun mengakuinya sebagai kiai.
Yang terpenting adalah pengakuan masyarakat, sedangkan keilmuan dan kepemimpinan adalah persoalan kedua. Baca juga: Muhammadiyah Tidak Diundang ke Sidang Isbat Kemenag Berbeda dengan itu, ulama adalah konsep teologis, yakni orang yang menguasai ilmu agama, bertakwa kepada Allah (yakhsyallaha), dan membawa misi kenabian (waratsatul anbiya’).
Kualitas keilmuan seseorang mungkin bisa diukur oleh manusia, tetapi dua kualitas lainnya (ketakwaan dan misi kenabian) hanya diketahui oleh Allah. “Dengan kata lain, apakah seseorang berhak disebut ulama atau tidak, dengan tiga kriteria itu, adalah urusan Allah yang Maha Tahu,” tutur Syafiq.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta