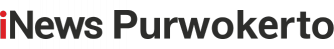Larangan Perkawinan Sokaraja-Purbalingga? Ternyata Ada Latar Belakang Sejarahnya

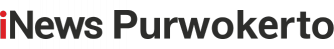

Berdasarkan isi dari naskah dari kedua versi tersebut, keduanya saling berlomba untuk berebut kebenaran atau dalam bahasa Priyadi disebut sebagai perebutan “legitimasi” dengan saling menjatuhkan satu sama lain demi kepentingan kelompoknya.
“Penuturan versi Sokaraja dan versi Purbalingga yang berbeda merupakan suatu gejala yang amat wajar dan secara pasti sering dijumpai dalam persoalan konflik di antara dua kubu. Masing-masing kubu berusaha melakukan pembenaran atas sikap dan perilakunya,” jelas Priyadi dalam jurnal ilmiahnya.
Dari keempat versi tersebut, Priyadi menemukan bahwa terdapat dua versi yang menyatakan bahwa konflik itu berakhir dengan damai dan kedua versi lainnya menyatakan bahwa konflik itu berakhir dengan konflik.
Salah satu versi yang memuat penyelesaian atas konflik antara Sokaraja-Purbalingga adalah versi Kutasari. Meskipun demikian, Priyadi menilai bahwa penyelesaian itu masih berbau konflik dengan ditemukannya tabu nikah.
“Tabu nikah adalah konflik sosial yang berlanjut hingga sekarang dan tidak dapat diketahui kapan berakhir, sementara masyarakat sekarang tidak lagi memahami konteks peristiwa yang telah terjadi. Mereka menjadi korban dari konflik orang-orang terdahulu,” imbuh Priyadi dalam jurnal imiahnya.
Menurut Priyadi, masyarakat dari kedua belah pihak meyakini bahwa pelanggaran atas tabu nikah tersebut berakibat fatal dalam kehidupan pasangan yang menikah. Ia juga menjelaskan bahwa awal mula terbentuknya keyakinan tersebut berdasarkan versi keempat adalah dari sebuah peristiwa lamaran seorang bangsawan Sokaraja terhadap putri Purbalingga.
Kala itu, pihak mempelai putri mengajukan syarat berupa tumpeng uceng. Seperti yang diketahui, uceng adalah jenis ikan yang hidup di sungai dan cukup langka populasinya.
Editor : EldeJoyosemito